
Oleh : Rudyspramz, MPI
Muhammadiyah sejak awal berdiri adalah gerakan dakwah. Ia tidak lahir sebagai reaksi emosional terhadap tradisi, tetapi sebagai ikhtiar sadar untuk menghadirkan Islam yang murni, rasional, dan membebaskan. Semangat amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid menjadi denyut nadinya. Namun dalam praktik dakwah, terutama ketika bersentuhan dengan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat di masyarakat, dakwah sering kali berada pada wilayah yang tidak hitam-putih.
Salah satu ruang dakwah yang paling sensitif adalah tradisi kematian. Di sana berkumpul duka, kehilangan, dan kebutuhan manusiawi untuk ditenangkan. Tidak sedikit warga masyarakat—bahkan yang secara ideologis simpati kepada Muhammadiyah—merasa ragu untuk mendekat karena khawatir tidak “lulus” secara keagamaan. Muhammadiyah kemudian dipersepsi sebagai gerakan yang benar, tetapi terasa jauh.
Sejak tahun 2002, Muhammadiyah telah mencanangkan dakwah kultural sebagai strategi dakwah yang lebih membumi. Namun hingga kini, konsep ini masih menjadi polemik, terutama ketika dikaitkan dengan praktik-praktik tradisi keagamaan seperti tahlilan dan yasinan dalam upacara kematian. Di sinilah dakwah Muhammadiyah diuji : bagaimana menjaga kemurnian ajaran Islam tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan?
Pendekatan bayani (tekstual) memberikan dasar yang tegas. Terdapat hadis yang dipahami melarang berkumpul-kumpul di malam kematian karena itu adalah niyahah (meratap), secara normatif, larangan ini jelas. Namun problem muncul ketika teks bertemu realitas sosial yang sangat berbeda dengan konteks Arab pada masa Rasulullah. Pertanyaan kritisnya adalah: apakah praktik berkumpul untuk berdoa hari ini identik dengan niyahah sebagaimana yang dilarang?
Niyahah pada masa Rasulullah adalah ratapan berlebihan, jeritan emosional yang mencerminkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Sementara dalam banyak praktik masyarakat hari ini, yang terjadi justru sebaliknya: ada ketenangan setelah doa, ada penguatan iman, ada solidaritas sosial. Jika esensi larangan niyahah adalah menolak sikap berlebihan dalam berduka, maka dakwah Muhammadiyah seharusnya fokus pada substansi itu, bukan semata pada bentuk luarnya.
Pendekatan burhani (kontekstual) mengajarkan bahwa dakwah harus membaca kebutuhan umat. Dalam suasana kematian, umat membutuhkan pendampingan spiritual, bukan penghakiman. Di sinilah peluang dakwah kultural Muhammadiyah terbuka lebar: menciptakan budaya baru yang tetap berpegang pada manhaj tarjih, namun menjawab kebutuhan psikologis dan sosial masyarakat.
Pengajian singkat, tadabbur Al-Qur’an, doa-doa yang shahih, dan nasihat keimanan dapat menjadi alternatif dakwah yang menenangkan tanpa harus terjebak pada ritual yang problematis secara akidah. Contoh inspiratif pernah ditunjukkan oleh almarhum Pak AR Muda di Lampung, yang dengan kesabaran dan kedekatan berhasil menggeser tradisi yasinan menjadi pengajian tafsir Al-Qur’an. Perubahan itu tidak lahir dari konfrontasi, melainkan dari keteladanan.
Lebih jauh, pendekatan irfani—pendekatan hati dan rasa—perlu mendapat tempat dalam dakwah Muhammadiyah. Menghibur keluarga yang berduka adalah bagian dari akhlak Islam. Dakwah yang kehilangan empati berisiko kehilangan umat. Mubaligh Muhammadiyah sejati bukanlah mereka yang berdiri di tepi sambil menunjuk kesalahan, tetapi mereka yang turun ke tengah umat, ikut mengalir, sambil tetap memegang prinsip agar umat tidak tenggelam.
Fakta di lapangan menunjukkan relasi warga Muhammadiyah dengan lingkungannya sangat beragam. Ada yang hadir aktif, ada yang hadir diam pakai doa sendiri, ada pula yang memilih menjauh namun ada juga yang diisi dengan pengajian dan doa. Namun tidak sedikit yang sebenarnya ingin menjadi bagian dari Muhammadiyah, tetapi terhalang oleh ketakutan terhadap pendekatan keagamaannya. Di sinilah dakwah kultural menemukan relevansinya sebagai jembatan, bukan kompromi akidah.
Jika Muhammadiyah ingin memperluas jamaahnya, dakwah kultural sesungguhnya memiliki basis nilai historis pada diri seorang kyai Ahmad Dahlan beliau adalah Pionir Aksi sebagai abdi dalem yang membidangi keagamaan mampu menjaga keharmonisan sosial dalam adat keraton dan masyarakat yang sinkretis.
Hari ini sinkretisme masih terasa kuat, dakwah kultural tidak cukup berhenti sebagai wacana dan beragam sikap keagamaan warga Muhammadiyah menyikapi relasi sosial keagamaan tersebut menjadi Diskursus Teori yang perlu disepakati, dilembagakan, dan diarahkan dalam koridor Institusionalisasi Manhaj Tarjih.
Budaya baru perlu diciptakan, bukan untuk mengaburkan kemurnian Islam, tetapi justru untuk menghadirkannya secara lebih membumi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh umat.
Pada akhirnya, dakwah bukan sekadar soal menyampaikan kebenaran, tetapi bagaimana kebenaran itu dapat didekati tanpa rasa takut. Menjaga kemurnian Islam dan merangkul kemanusiaan bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru di sanalah dakwah Muhammadiyah menemukan wajahnya yang paling otentik.
wallahu a'lam
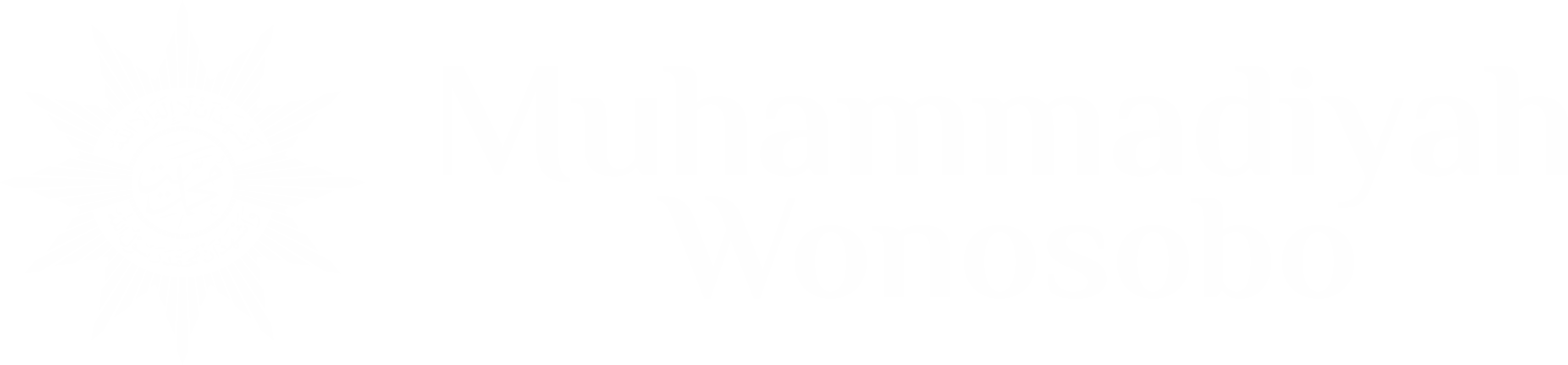




Comments
very good