
Oleh : Rudyspramz, MPI
Diskursus tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam selalu menghadirkan perdebatan yang dinamis. Di satu sisi, ada pembacaan tekstual yang menekankan perbedaan peran berdasarkan nash Al-Qur’an dan Sunnah—terkait pakaian, poligami, warisan, maupun kesaksian. Di sisi lain, muncul kritik modernitas yang mempertanyakan aspek keadilan dan kesetaraan gender. Dalam ruang dialektika inilah tokoh seperti Zakir Naik sering tampil menjelaskan Islam secara argumentatif dan komprehensif, menekankan bahwa perbedaan dalam Islam bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan pengakuan atas fitrah dan fungsi sosial yang saling melengkapi.
Perbedaan sebagai Komplementaritas, Bukan Hierarki, Secara teologis, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai setara dalam kemuliaan spiritual (QS. Al-Hujurat: 13), namun berbeda dalam sejumlah tanggung jawab sosial tertentu. Perbedaan dalam warisan, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari struktur tanggung jawab nafkah dalam sistem keluarga Islam klasik. Demikian pula soal kesaksian dalam konteks tertentu yang terkait dengan konstruksi sosial dan literasi ekonomi pada masa turunnya wahyu.
Pendekatan ilmiah terhadap ayat-ayat tersebut mengharuskan kita membedakan antara : Nilai normatif-universal (maqashid: keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat), dan Instrumen sosiologis-historis yang kontekstual.
Dalam kerangka ini, perbedaan bukanlah subordinasi, melainkan functional differentiation, pembedaan fungsi dalam sistem sosial yang saling melengkapi (complementary partnership).
Ketegangan antara Konservatisme dan Liberalisme dalam perjalanan sejarah, terdapat kecenderungan ekstrem di dua kutub : Konservatisme berlebihan, yang membatasi perempuan secara kaku: pakaian serba tertutup tanpa ruang ijtihad budaya, pelarangan pendidikan, pembatasan ruang publik, bahkan praktik poligami yang reduktif menjadi legitimasi nafsu.
Liberalisme tanpa batas, yang melepaskan nilai agama atas nama kebebasan dan modernitas, hingga identitas spiritual tercerabut dari akar normatifnya.
Kedua ekstrem ini sama-sama problematik. Yang pertama berpotensi mengerdilkan maqashid syariah, sementara yang kedua mengabaikan fondasi etik-transendental Islam.
Muhammadiyah telah merumuskan Jalan Wasathiyah Peradaban Islam lewat pendekatan yang relatif moderat melalui konsep Wasathiyah Islam, Ijtihad dan Tajdid, serta visi Rahmatan lil ‘Alamin sebagaimana tertuang dalam Risalah Islam Berkemajuan (RIB).
Wasathiyah bukan kompromi nilai, melainkan keseimbangan antara teks dan konteks. Ijtihad bukan pembebasan liar, tetapi upaya metodologis membaca realitas baru dengan perangkat ushul fiqh dan maqashid syariah. Tajdid bukan mengubah agama, melainkan memurnikan sekaligus memajukan pemahaman agar tetap relevan sepanjang zaman.
Dalam perspektif ini : Pendidikan perempuan adalah keniscayaan karena ilmu adalah kewajiban universal, partisipasi publik perempuan sah sepanjang menjaga etika dan kemaslahatan, pakaian adalah ekspresi syar’i yang memperhatikan prinsip kesopanan dan budaya setempat tanpa kehilangan substansi, poligami dipahami sebagai rukhshah (dispensasi), bukan norma ideal, dengan syarat keadilan yang sangat berat.
Refleksi Epistemologis dalam Relasi agama dan modernitas bukanlah pertarungan biner, melainkan dialog epistemologis. Agama memberi fondasi moral-transenden, sementara modernitas menawarkan perangkat rasional dan institusional. Ketika keduanya dipertemukan melalui ijtihad yang bertanggung jawab, lahirlah peradaban yang berkeadilan dan berkemajuan.
Islam tidak menghapus perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarahkannya dalam sistem etika yang menjaga martabat. Di sinilah pentingnya keseimbangan: menjaga fitrah tanpa membelenggu potensi, membuka ruang publik tanpa menghilangkan akar spiritual.
Perempuan dalam Islam bukan objek perlindungan pasif, melainkan subjek bermartabat yang memiliki hak spiritual, intelektual, dan sosial. Tantangannya hari ini bukan memilih antara konservatif atau liberal, melainkan membangun sintesis keilmuan yang berlandaskan maqashid syariah, kontekstualisasi sejarah, dan komitmen pada keadilan.
Jalan tengah—wasathiyah—bukan posisi aman di antara dua ekstrem, tetapi posisi sadar yang menuntut kedalaman ilmu, keluasan hati, dan keberanian moral.
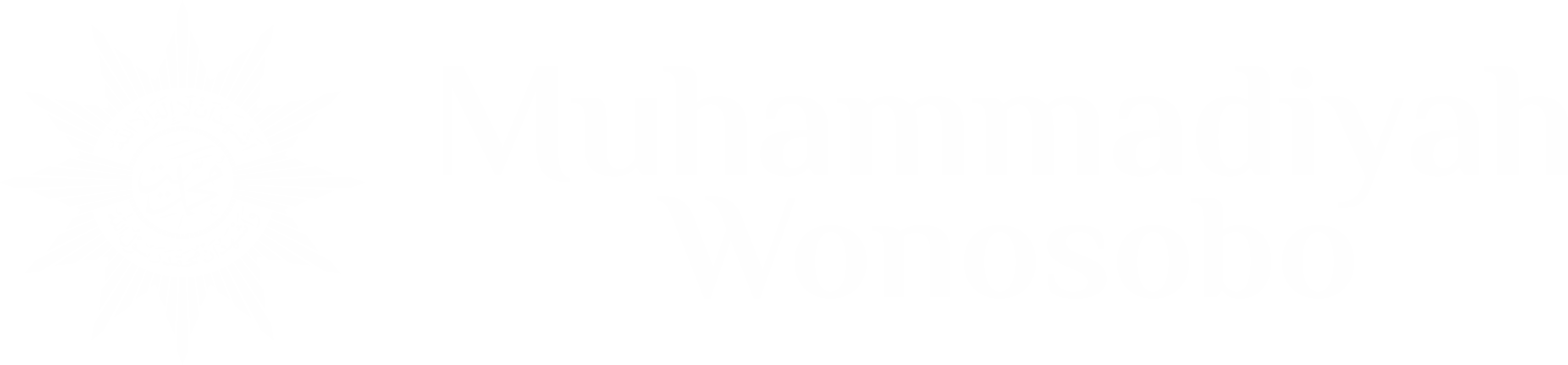




Comments
No comments yet. Be the first to comment!